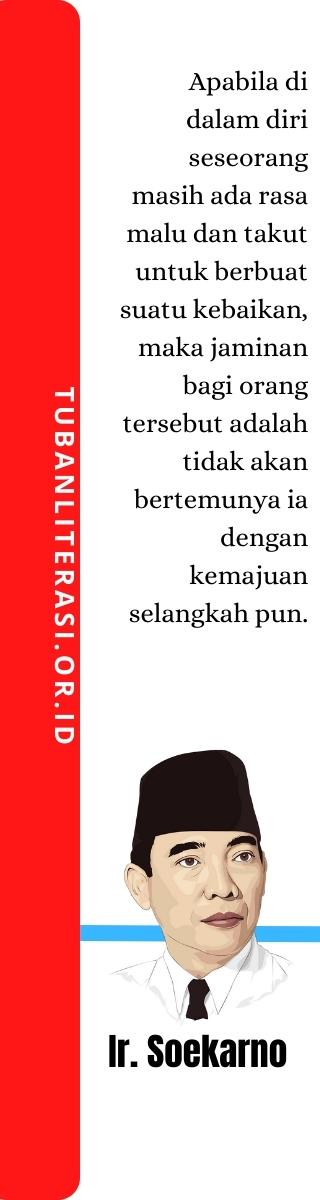Oleh: Wahyu Eka S.
Tuban Literasi – Pada bulan Agustus 2017, Mbah Parman ditangkap polisi hutan sebagai sebuah kesatuan yang tersinkron dengan Perhutani. Beliau ditangkap karena dianggap mencuri pohon di wilayah kelola Perhutani BRPH Kejuron, BKPH Bangilan, KPH Jatirogo. Berdasarkan data yang terhimpun luas di banyak berita online, Mbah Parman 64 tahun, didakwa mengambil tanpa izin satu batang kayu jati, dengan ukuran 300 cm x 13 cm dengan berat sekitar 0,049 meter kubik.
Argumentasi KPH Perhutani Jatirogo memperkarakan Mbah Parman, karena mereka mengklaim mengalami kerugian sebesar Rp 263.829. Sejak 22 Agustus 2017, Mbah Parman sudah ditahan untuk menjalani proses penyidikan. Hingga pada putusan persidangan pada 21 Desember 2017, seperti yang dilansir dari Jawa Pos online, Mbah Parman dijatuhi vonis empat bulan penjara dikurangi masa tahanan.
Sementara tuntutan awal pihak jaksa penuntut umum mengacu pada pasal 82 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan ancaman hukumannya, minim selama tiga bulan dan paling lama dua tahun atau denda minimal sebesar 500 ribu, maksimal sebesar 500 juta rupiah.
Secara dasar dalam aturan legal memang Mbah Parman terbukti melakukan tindakan illegal, dengan mengambil kayu jati tanpa izin penguasa land lord atas nama Perhutani. Sehingga barang siapa yang tanpa izin melakukan tindakan tanpa titah land lord, maka dia bersalah dan mutlak harus diberikan hukuman.
Namun di sisi lain kita akan melihat bagaimana persoalan yang sistemik sering menyasar warga sekitar wilayah hutan. Mereka sering terlibat konflik dengan penguasa hutan, terutama persoalan dalam pemanfaatan hutan. Bahkan pada satu pola, mereka sering dituduh menjadi biang kerok kerusakan hutan.
Peristiwa serupa juga terjadi di banyak daerah, masih hangat diingatan kita bagaimana petani Surokonto Wetan dikriminalisasi karena dianggap menyerobot tanah ruislag, antara Semen Indonesia dengan Perhutani KPH Kendal. Kyai Nur Aziz diputus vonis delapan tahun dan denda delapan miliar, karena dianggap provokator penyerobotan tanah milik yang mulia land lord.
Sementara tidak jauh dari Mbah Parman, di Jember Poniran dituduh menyerobot atau bahasa halusnya perambahan lahan milik Perhutani KPH Perhutani Jember. Padahal dalam fakta, Poniran menggarap lahan seluas 80 x 50 meter persegi yang dalam wilayah perjanjian kerja sama antara KPH Perhutani Jember dengan LMDH Sabrang. Kasus-kasus serupa masih banyak dan menjadi momok warga adat maupun mereka yang tinggal di sekitar wilayah hutan.
Persoalan yang menimpa banyaknya petani, warga lokal di sekitar wilayah kelola hutan, berakar dari undang-undang P3H yang disahkan tahun 2013. Memang peraturan tersebut mengandung sebuah perspektif agung tentang perlindungan hutan. Namun dalam praktiknya selalu menyasar warga lokal, petani dan segenap elemen masyarakat sekitar hutan. Konsorsium Pembaruan Agraria mencatat setelah dua tahun, yaitu sekitar tahun 2015. Terdapat 10 kasus yang menjerat warga lokal (masyarakat adat), petani dan buruh.
Anehnya tak ada nama pemain besar yang acap kali merusak hutan, menghancurkan hutan yang harusnya dijaga. Contoh kasus di Bengkulu, tercatat empat warga adat Semende Agung harus menerima kenyataan berat, mereka divonis dengan hukuman maksimal tiga tahun penjara dan denda sekitar Rp1,5 miliar tiap kepala. Warga adat Semende Agung dengan gegabah dituduh merusak Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Jika ditelaah secara historis mereka telah hidup secara turun menurun di kawasan tersebut, sebelum ditetapkan sebagai kawasan konservasi dengan status Taman Nasional.
Sejatinya apa yang dialami Mbah Parman juga dirasakan oleh banyak masyarakat, bahwa mereka dialienasikan dari hutannya. Sering dianggap sebagai biang kerok perusakan hutan, padahal jika ditelaah mendalam hanya segelintir yang merusak, tentu kebanyakan mayoritas dilakukan oleh pemain besar. UU P3H seakan menjadi momok menakutkan bagi warga, yang hidup di wilayah sekitar hutan. Seakan-akan peraturan tersebut bukan malah melindungi hutan, tetapi berupaya memisahkan warga dengan hutannya.
Pengelolaan hutan sebenarnya tanpa Perhutani pun masyarakat mampu mengelola, mengingat secara adat dan budaya mereka mempunyai nilai-nilai sendiri yang teruji selama ratusan tahun. Namun kemudian nilai itu rusak karena syahwat kapital, yang melakukan perampasan tanah untuk industrialisasi, sehingga dampaknya ialah banyak hutan yang menjadi sasaran okupasi lahan.
Persoalan lain ialah banyaknya industri ekstraktif baik dalam konteks mineral maupun sawit yang kerap merampas lahan hutan. Dengan dalih investasi, serta keuntungan Negara masyarakat semakin dialienasikan dengan alamnya, bahkan pada konteks ini secara substansial mengakibatkan rusaknya beberapa kawasan hutan.
Jika melihat dalam perspektif historis, era Sukarno mengizinkan masyarakat mengelola hutan dengan batasan-batasan tertentu, seperti tidak mengkomersialkannya, tentu semua dengan tujuan mewujudkan masyarakat yang adil sesuai konteks kemaslahatan warga (umat). Era Gus Dur pernah membuka akses hutan untuk masyarakat, dengan pengawasan Negara, tentu hal ini ditujukan untuk mengembalikan suatu paradigma bahwa lingkungan hidup dan manusia harus seimbang.
Berdasarkan basis konstitusi dasar pasal 33 UUD 1945, maka pengelolaan suatu kawasan harus berdasarkan asas gotong royong, serta Negara sebagai kontrol dengan menerapkan nilai-nilai perlindungan sesuai dengan kearifan lokal. Jika ditilik pada masa orde baru, fakta pengelolaan hutan mengalami transformasi yang cukup radikal dengan mementingkan hak pemodal daripada kepentingan masyarakat.
Hak Guna Usaha (HGU) maupun Hutan Tanaman Industri (HTI), merupakan bukti jika era orde baru lebih mementingkan pemodal, dan parahnya sekarang konsep-konsep demikian kembali dijalankan. Jelas sudah amanah konstitusi sangat jauh dari harapan.
Mengacu pada perspektif islam. Seharusnya pengelolaan hutan harus didudukan dengan memegang prinsip kemaslahatan umat dan kelestarian lingkungan. Menurut jurnal dari Abu Rokhmad yang berjudul Studi Tentang Konflik Tanah Hutan Negara dan Resolusinya dalam Perspektif Fiqh. Menuturkan Kriteria maslahah ammah yang dirumuskan Wahbah al-Zuhaili. Hutan dan pengelolaannya harus bermanfaat yang dapat dinikmati oleh seluruh sebagian besar masyarakat.
Selanjutnya pengelolaan harus sesuai dengan tujuan syariah, sebagaimana yang terhimpun dalam alkulliyyat al-khamsah, sesuai dengan pasal 33 UUD 1945, yang diimplementasikan dalam UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Dengan argumentasi, semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Manfaat dari pengelolaan hutan yang dimaksud harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh umat, bukan hanya sebatas klaim sepihak saja atau wahmi (perkiraan) tanpa dasar. Persoalan hutan baik pengelolaan harus mencakup keadilan yang bersifat sosial-ekologis, berdasar dari al-Quran, Hadits dan Ushul Fiqh. Pada intinya tata kelola hutan tidak boleh berkontradiksi dengan kepentingan umum sesungguhnya, yaitu masyarakat sekitar hutan.
*penulis adalah nahdliyin independen